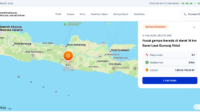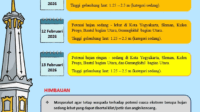Seperti dua pendekar dalam kisah perang Jawa, Megawati dan Jokowi kini berada di titik sampyuh—sebuah pertarungan di mana keduanya saling menebas, tetapi juga menanggung luka yang bisa melemahkan mereka bersama.
Dulu, mereka berada dalam satu perahu, berlayar di samudra politik dengan tujuan yang sama. Megawati adalah sang nahkoda, pemegang kompas ideologis PDIP, sementara Jokowi adalah awak kapal terbaiknya, yang mampu menavigasi gelombang politik hingga mencapai puncak kekuasaan. Selama bertahun-tahun, mereka berbagi strategi, menyusun langkah, dan memahami setiap kelebihan serta kelemahan masing-masing.
Namun, perbedaan visi dan kepentingan kini menjelma menjadi badai. Jokowi yang dulunya dianggap sebagai kader loyal, kini memiliki kekuatan politiknya sendiri. Ia tidak lagi sekadar pelaksana garis partai, tetapi telah membangun jejaring kekuasaan yang membuatnya mampu berdiri sendiri—dan bahkan menantang otoritas Megawati.
Di sisi lain, Megawati adalah petarung lama yang telah terbiasa menghadapi pengkhianatan dan perubahan peta politik. Ia melihat Jokowi bukan lagi sebagai sekutu, tetapi sebagai ancaman bagi warisan politik yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Dalam perspektifnya, Jokowi telah melangkah terlalu jauh, melampaui batas loyalitas terhadap partai yang membesarkannya.
Maka, pertempuran tak terelakkan. Saling serang di medan politik terjadi dalam bentuk sinyal keras, pernyataan tajam, hingga perebutan pengaruh dalam partai dan pemerintahan. PDIP mulai mempertegas garisnya, sementara Jokowi semakin mengukuhkan kekuatan di luar kendali partai.
Namun, seperti dalam perang Jawa, sampyuh bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah, tetapi bagaimana keduanya bisa mengalami kehancuran bersama. Jika konflik ini terus membesar, Megawati bisa kehilangan kendali atas partainya, sementara Jokowi bisa terisolasi tanpa kendaraan politik yang solid. Di tengah perseteruan mereka, pihak ketiga mungkin justru menjadi pemenang sejati.
Akhir dari duel ini masih belum jelas. Apakah mereka akan menemukan jalan damai, atau justru terus bertempur hingga keduanya melemah? Seperti halnya kisah dalam sejarah, pertarungan di puncak kekuasaan selalu membawa risiko: menang tanpa kawan, kalah tanpa belas kasihan.
Tulisan iini hanyalah metafora yang mengingatkan bagaimana perseteruan kedua kubu bisa melemah bersama akibat konflik berkepanjangan
ditulis oleh : Heru Warsito, jurnalis Echannel